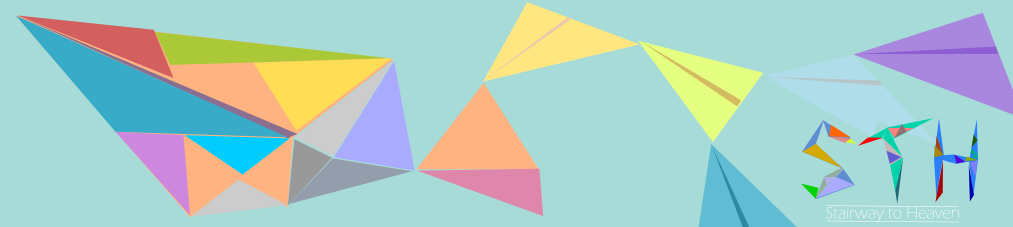Cara untuk merasa itu, punya hati.
Saat hati tak merasa, maka kau tak punya dunia.
Hidup dalam hiperbola, bukan
tanpa percuma, hidup itu kanvas, dan lukisan itu bagaimana cara seorang
menggambar hidupnya. Putih, hijau, kuning, merah, semuanya, berbaur, dan
warnamu kan menghitam. Hanya pilih satu warna dasarmu, dan lukislah diatasnya,
menurut instinc, hati, nurani, semua tentangmu. Be yourself.
Hati itu unik, sama seperti
indra, beda dari semua indra hanyalah impuls yang diterimanya. Berbeda dengan
mata, telinga, lidah, kulit, kesemua indra menerima rangsang dari suatu materi,
yang jelas bentuk dan rupanya. Tapi hati
itu bagaimana? Terkadang bukanlah impuls materi yang diterimanya. Seperti
perasaan, emosi, persepsi, kesemuanya bukanlah benda yang terukur atau bisa
diukur.
Hati itu bukan liver, bukan juga
jantung, dan bukan juga otak, bagian yang tak terjamah, mungkin begitu kecil.
Tapi bagaimana bisa menampung semesta?
Kompressi Data, mungkin itu kata yang tepat untuk proyekku ini.
Mengkompress seluruh data semesta dalam hidupku, dalam sebuah prosa, ya puisi.
Bukan tanpa alasan, atau iseng, hanyalah tugas dari guru mata pelajaran bahasa
Indonesia, mengingat pelajaran kali ini telah masuk dalam bab sastra. Mungkin
ide yang berlebihan, ku mulai terhanyut.
Tapi bagaimana caranya?
Oke,
pertama, buat temanya. Temanya yaitu, ‘hidup’, ‘hidupku’.
Sore itu, semesta terhalang
mendung dilangit yang melengkung, beberapa menit termenung.
“Ah,
semesta. Semesta itu bukan aku saja. Orang lain ikut andil dalam ini. “,
terucap dari mulutku.
Sejak itu, tema puisiku menjadi ‘Hidup’. Lebih universal, mencakup semua
orang. Maka sejak saat itu juga, ku mulai menanyai, pada temanku, tetangga,
semua orang yang dijumpai, oleh pertanyaan yang sama.
“Jika hidup mu itu diringkas
dalam satu kalimat, kalimat apa itu?.”, Tanyaku pada suatu pagi di sebuah
terminal pada salah seorang temanku. Maka selanjutnya, dapat ditebak, hanya
diam beberapa detik , dan terjawab.
“Tau ah, gak penting.”, lalu
pergi.
“Hidup itu, ini.”, jawab preman
terminal sambil menggerakkan jarinya, didepan mataku. Aku tahu isyarat itu,
uang. Isyarat itu menjadi jawaban yang hits setelah aku bertanya kesekian
kalinya pada tukang ojek, supir angkot, tukang gorengan, penjaga warung,
pengamen. Ah, semuanya sama saja.
Materialistis, semuanya hanya
inginkan uang. Apa yang bisa mereka lakukan dengan uang itu, apa mereka bisa
membeli dunia ini, apa yang mereka lakukan jika mereka mempunyai uang setinggi
gunung. Mungkin salahku juga karena menanyakan pada orang- orang yang sedang
butuh uang, pada orang yang sedang bekerja, mungkin fikiran mereka terisi oleh
materi belaka, hanya untuk mencukupi hidup mereka, menghidupi anak istri
mereka.
Seperti pengemis yang tengadah
di trotoar dengan topi usang yang menghadap langit, muka memelas, hanya
berharap dan memohon, uang akan jatuh menimpa dan mengisi topi mereka itu. Tak
peduli uang itu berasal dari mana, dari hati yan iba, atau uluran yang
bersahaja, maupun niat muka dua, kesemuanya sama saja. Mungkin ditengah
penantian mereka, tersirat permohonan maupun mimpi semoga uang kan jatuh dari
langit, awan kan turunkan duit.
Preman terminal sama saja, hanya
sedikit bermodal sama seperti artis atau
model. Cukup tampang garang, dan pasang akting brutal, duit pun masuk ke
kantongnya beberapa lembar. Uang, dan uang, tak ada tujuan lain dihidupnya,
mereka hanya hidup untuk hidup.
Jika uang adalah hidup mereka.
Maka aku kan tanyakan pada orang lain, yang ku kira cocok. Yang tak ada uang
difikirannya, yang benar- benar dapat menjawab pertanyaanku ini, dan ku kan
terpuaskan.
Berlanjut dalam pencarian
jawaban atas pertanyaan yang sama. Uang mungkin hanya sampah yang mengotori
fikiran seseorang, maka. Aku berfikir untuk mencari orang yang bersih dari uang
dikepalanya. Tapi, itu sulit, semua orang butuh uang dalam hidupnya, tak ada
orang yang tak mementingkan uang, tak ada orang yang tak mau diberi uang. Salah
satu jalannya yaitu mencari orang yang sudah punya banyak uang, mungkin terlalu
banyak sehingga ia tak usah memikirkan bagaimana caranya ia mendapatkan uang.
Aku butuh seorang konglomerat.
Paul, pemuda yang kutemui, dia
adalah anak orang kaya, saking kayanya, ia tak pernah memikirkan ia kan jadi
apa. Jangankan bekerja, kuliah pun seolah tak penting baginya. Karena biarpun
begitu masa depannya telah terjamin oleh kekayaan orang tuanya. Setiap hari
kerjanya hanya nongkrong- nongkrong dengan teman- temannya di bengkel motor
yang sering ku lewati setiap pagi. Atau terkadang, berkeliling kota dengan
mobil sport ferrarinya, main di klub atau kafe. Semua hidup dijalaninya dengan
kesenangan. Mungkin ia orang yang tepat untuk dapat memberikan jawaban tentang
apa itu hidup.
“Akh, men. Lo pengen tau hidup
itu apa. Nanti sore, gue tunjukkin ama lo hidup itu apa.”, jawabnya.
Malam harinya, aku duduk di
mobil sport ferrari kebanggaan Paul. Entah kemana aku ‘kan dibawa. Yang
tersirat difikiran hanyalah aku ingin tahu hidup itu apa, versi Paul tentunya. Mobil
itu melesat ditengah hiruk pikuk kendaraan, dan remang malam. Dan setelah
terhenti, kakiku ku langkahkan dalam beberapa langkah, semuanya berubah menjadi
dentum musik yang menggugah kaki tuk berjinjit, yang menggoda tangan ikut
meliuk. Tapi, tubuhku tak ikut meliuk, ditengah sorotan cahaya laser yang
memecah remang ruangan. Inikah hidup itu?
Selanjutnya, sebotol minuman,
berdiri jelas dihadapanku, diatas meja bar klub itu.
“Gue pesen yang paling mahal
buat lo. Coba!” suruhnya, sambil menuangkan cairan botol itu dalam gelas.
Ku tak tahu harus bagaimana saat
tangannya mulai menyodorkan gelas itu. Terus memaksaku untuk masuk dalam arti
hidup sebenarnya versi dirinya. Dan gelas itu makin dekat kemulutku. Dan
tertelan, teguk demi teguk.
“JD, Lemonade, rasa lemon.”,
ucap Paul.
“Lo
sekarang tahu, arti hidup bagi gue itu apa.”, ujarnya lagi sambil memgang
gelasnya.
Aku
hanya diam, sambil menatapnya. “Do what you will.”, sambungnya lagi.
Do what you will, lakukan apa yang kau inginkan. Sependek itu? Bagaimana jika aku tak
bisa melakukannya. Jika aku ingin mengkerdilkan semesta, apa yang harus ku lakukan?.
Jika aku ingi tahu makna hidup apa yang harus kulakukan. Ini masih buntu, dan
masih butuh banyak penjelasan.
Sebelum
mataku jauh lebih berat lagi, dan sebelum ku mulai jatuh karena beban kepala.
Ku tinggalkan remang, sorot, dan hiruk pikuk ini menigggalkan Paul. Ah, inikah
hidup baginya itu, hanya kesenangan, akh, monoton, gak bakal seru, fikirku.
Paul, kau tak berguna lagi, hidupmu terlalu dangkal, maknanya. Saat semuanya
mulai membebani kepala. Menurunkan kelopak mata hingga mulai berat, dan saat itu
kutahu hanya ada gelap. Selanjutnya aku tersadar dikasur empuk, dikamarku.
Jika
hidup itu hanya kesenangan, apa yang lain juga merasakan? Jika hidup itu hanya
kesenangan, maka hanya dangkal, tak ada rasa yang lain. Akh, membosankan. Saat
itu aku tersadar, bahwa Paul juga tak terlepas dari materi, tak terlepas dari
uang, karena ia punya segalanya, maka iapun dapat segalanya. Do what you will.
Kemanakah
akan kutanyakan lagi. Mungkin pada orang yang terlepas dari kesenangan, orang
susah? Ah, tidak, sama halnya seperti pengemis atau supir angkot, mereka hanya
inginkan uang, lalu pada siapa?.
Aku
tahu, pada siapa kuharus bertanya.
Sore
itu, adzan shalat Ashar telah berkumandang, saat itu juga telah ku tanggalkan
sandal diantara sandal lainnya, hanya ada tiga pasang. Mengapa begitu sepi,
mungkin tak seperti jam- jam shalat lainnya, tak seramai isya aitau maghrib.
Setelah berwudlu, langsung ku langkahkan melewati gerbang majid itu.
Hanya
ada satu shaff, dengan dua jama’ah, dan jamaah ketiga sedang melangkah menuju
barisan, sebelum shalatnya ketinggalan. Satu pedagan gorengan keliling, satu
orang berkemeja rapi, yang diimami oleh seorang muadzin yang sering adzan di
masjid ini.
Kekhusyukan
mengalir.
Setelah
shalat selesai, kedua jama’ah langsung saja pergi. Dan yang tersisa hanya aku,
dan imam. Ia adalah Soleh, pengurus masjid ini, dan sekaligus muadzin disini,
sedang melafalkan sesuatu dan aku hanya mengamininya, menunggu hingga selesai.
Dan selesailah, jabatan tangannya mengayalami dengan lembut, besrta senyum sapa
yang tertuju kearahku.
Perbincangan
dmulai, saat itu.
“Jika
hidup mu itu diringkas dalam satu kalimat, kalimat apa itu?.”, tanyaku kesekian
kalinya pada orang yang berbeda.
“AsyhadualLaailaha
illallah, Wa asyhaduanna Muhammadarrasulullah.”, ucapnya.
“Hidup
itu, Cuma satu kali, dan kalau hidupku itu diringkas dalam satu kalimat, Cuma
kalimat itu yang kuinginkan. Karena sebagai muslim, hidupnya pasti ditujukan
Cuma buat itu, mempertahankan iman. Hidupnya pasti gak bakal berguna tanpa
kenal kalimat itu, karena hidup kita didunia ini ya, bekal menuju akhirat
sana.”, jelasnya.
“Jadi,
hidup mu ini susah atau senang?” tanyaku.
“Alhamdulillah.
Jika kita punya iman dihati, pasti hanya tenang yang ada. Tapi semua rasa juga
ada disana, takut, marah, benci, senang, gembira, damai, pokoknya hati kita
punya segalanya.”
“Takut
murka Alloh SWT, marah, benci ya pada shaitan, senang apabila selalu mengingat
rezeki dan nikmat dari-Nya, damai saat menikmati kehkusyukan saat shalat. Ah,
semuanya ada dalam iman.”, sore itu berlalu sangat panjang, seolah merasa
tercerahkan oleh sesuatu. Difikiranku terngiang rentetan kata yang membentuk
suatu prosa.
Hidup itu, jalan berkabut yang harus dilalui.
Hati itu obor,
Dan iman, adalah cahaya api yang menerangi.
Puisi
pertamaku telah, jadi.
Posted by Unknown in short story
(c) nurhidayat notes 2013. Diberdayakan oleh Blogger.